Bayangin dunia tahun 1990-an, tapi bukan yang kita kenal—ini versi alternatif, penuh reruntuhan sisa perang besar antara manusia dan mesin. Dunia di film The Electric State adalah campuran unik antara nostalgia era analog—kayak TV tabung, VHS, dan mobil-mobil tua—dengan teknologi super canggih yang udah terbengkalai. Visualnya mirip mimpi buruk dari masa depan yang dibungkus dalam estetika masa lalu. Di tengah kekacauan ini, kita kenalan sama Michelle (Millie Bobby Brown), remaja cewek tangguh yang jalan sendirian di dunia sunyi nan rusak. Tujuan utamanya sederhana tapi menyayat: nyari adik laki-lakinya, Christopher, yang katanya udah meninggal di tengah kekacauan, tapi hatinya bilang dia masih hidup.
Michelle punya satu teman dalam perjalanan ini: Cosmo, robot kecil dan usang tapi punya ekspresi yang somehow bikin penonton simpati. Ternyata, Cosmo bukan sembarang robot—dia punya koneksi langsung ke Christopher lewat perangkat bernama Neurocaster, alat telepati digital yang dulu dipakai untuk komunikasi canggih. Cosmo muncul dari tempat misterius dan jadi semacam petunjuk pertama bahwa Christopher mungkin masih eksis, entah sebagai manusia atau sesuatu yang lain. Di sinilah perjalanan Michelle mulai terasa kayak gabungan antara road trip, misteri sci-fi, dan misi penyelamatan yang makin gila dari waktu ke waktu.
Nggak lama, mereka ketemu Keats (Chris Pratt), mantan tentara yang sekarang hidup sebagai penyelundup barang antik dan informasi. Keats awalnya kelihatan skeptis dan ogah ribet, tapi akhirnya luluh juga sama tekad dan keberanian Michelle. Ia pun ikut dalam perjalanan mereka, nyetir truk rongsokan sambil ngebantu mereka hindarin ancaman, baik dari manusia maupun robot-robot rusak yang berkeliaran di luar zona aman. Sepanjang jalan, mereka bertiga menjelajahi reruntuhan kota-kota besar, stasiun militer yang ditinggalkan, hingga komunitas robot yang hidup dalam keterasingan. Makin jauh mereka melangkah, makin banyak petunjuk bahwa dunia ini nggak cuma rusak—tapi sedang dikuasai dari balik layar oleh sesuatu yang jauh lebih gelap.
Millie sendiri sebenarnya punya potensi gede, tapi aktingnya di sini cenderung flat, kurang “nendang” di momen-momen emosional. Chris Pratt? Masih bawa vibes Star-Lord tapi versi capek. Karakter Keats yang dia mainin kayak cuma numpang lewat buat kasih efek lucu dan jadi sidekick, tanpa perkembangan karakter yang jelas. Cosmo, robot yang seharusnya jadi jembatan emosional antara manusia dan mesin, juga kurang berhasil bikin penonton merasa koneksi yang kuat. Bahkan hubungan Michelle dan Christopher yang jadi inti cerita, nggak berhasil ngebangun ketegangan atau kedalaman yang menyentuh.
Kalau dibandingin sama film-film yang punya vibe mirip, kayak The Iron Giant atau Chappie, The Electric State kalah jauh dari sisi storytelling dan emotional weight. The Iron Giant sukses banget bikin kita sayang sama karakternya dalam waktu singkat, dan bikin air mata netes pas ending-nya. Chappie juga berhasil nunjukin sisi manusiawi dari robot yang “lahir” di dunia yang keras. The Electric State punya semua bahan buat bikin cerita menyentuh, tapi entah kenapa kayak nggak bisa ngeraciknya dengan pas.
Dengan budget gede—katanya sampai $320 juta—film ini jadi salah satu produksi termahal Netflix. Tapi ya, high budget nggak selalu berarti high quality. The Electric State bukannya nggak punya potensi, tapi potensinya keburu terkubur sama naskah yang lemah dan pacing cerita yang membosankan. Skor Rotten Tomatoes-nya juga cuma 15%, yang jujur aja, cukup bikin syok untuk film sebesar ini. Banyak kritikus juga bilang film ini ambisius tapi kurang hati.
Kesimpulannya, The Electric State adalah contoh klasik dari “visual doang nggak cukup”. Dunia dan konsepnya keren, idenya kuat, tapi semua itu nggak punya dampak kalau ceritanya nggak bisa nyentuh penonton. Buat yang pengin nonton film sci-fi dengan vibe petualangan dan robot-robot keren, mungkin film ini masih worth buat dilirik. Tapi kalau kamu nyari sesuatu yang emosional dan meaningful kayak The Iron Giant, mungkin lebih baik cari alternatif lain. Film ini seperti peta indah menuju destinasi yang salah—seru dilihat, tapi bikin bingung mau ke mana.





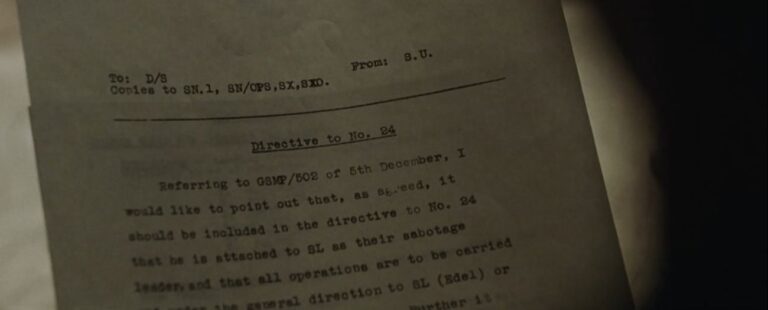





Leave a Reply